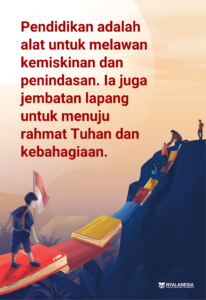Hari yang cerah. Matahari bersinar tepat searah lemparan tombak. Pasir-pasir pantai yang putih tampak menyilaukan mata. Musim kemarau sudah datang, menggantikan musim hujan yang basah dan lembab. Warga desa tampak berduyun-duyun ke pantai, demi mememburu kerang perceng. Para warga dengan antusias membawa sekop serta wadah, untuk menyempurnakan buruannya.
Warga desa menyebutnya perceng, namun ada juga yang menyebutnya kerang siput gonggong. Kerang ini tersebar luas di pulau. Ketika musim kemarau tiba, selain para warga di pulau, warga luar pulau pun turut memeriahkan memburu kerang tersebut.
Dengan mengendarai sepeda motor butut kesayanganku, aku secepatnya menarik gas untuk mencapai pantai dengan cepat. Tersebar kabar dari teman-teman, beberapa orang sudah memenuhi pantai, tanpa ba-bi-bu aku langsung tancap gas menuju pantai.
Langit begitu cerah, angin laut perlahan menggerayangi tubuh, membuat aku sedikit menggigil. Air ombak menyentuh kaki kasarku. Tatapanku lurus memperhatikan pasir-pasir yang aku pijaki, aku mulai mengambil sekop, meraba-raba dengan cermat, hanya pasir yang memenuhi tanganku. Aku ulangi lagi hingga kelima kali, akhirnya aku mendapatkan perceng pertamaku. Perasaan bangga menyelimuti, anganku menampakkan perasaan Emak yang bahagia atas pendapatan perceng ku.
Tak terasa aku sudah berjalan hingga ujung pantai, sangat jauh dari pemukiman, hanya pohon-pohon cemara yang rimbun dan pohon-pohon bakau. Tampak suasana mulai agak gelap, matahari yang sedari pagi menampakkan diri, akhirnya akan membenamkan dirinya ke pangkuan semesta.
Aku mulai merinding tak karuan. Di sekeliling sangat sepi, hanya suara ombak dan kicauan burung di tengah rimbun pohon. Aku lihati tempat wadah hasil buruanku, ternyata sudah terisi penuh. Pikirku aku berjalan disekitaran pantai, ternyata aku berjalan ke tempat yang seharusnya tidak boleh dilewati. Warga desa menyebutnya panyeppen yang artinya tempat menyepikan diri. Konon, tempat ini merupakan tempat kesukaan orang-orang pencari hal gaib, mereka akan bersemedi disini, menghindari diri dari lingkungan luar.
Sayup-sayup aku mendengar suara wanita yang sedang bernyanyi, suaranya bergetar merdu. Bulu kudukku semakin merinding, diantara penasaran dan takut. Aku berjalan menjauhi tempat ini.
“Hei, mau kemana?”.
Sontak aku terdiam kaget, suara panggilan itu sangat dekat. Aku membalikkan badan, sosok perempuan muda yang sangat cantik memandangiku, lipatan kelopak matanya begitu indah, wajah halusnya begitu cemerlang, dan bibirnya begitu ranum.
Aku tergagap sambil menunjuk arah sembarang. Ia hanya tersenyum manis dan mengangguk.
“Kamu siapa?”, tanyaku.
“Aku Hawa”, ujarnya lembut. Aroma melati semerbak wangi dari tubuhnya.
Lantas dia mengantarkanku pulang, menunjukkan jalan setapak yang dipenuhi semak belukar. Aku berjalan beriringan, ia di belakangku. Kita hanya diam tanpa berkata apapun. Aku semakin mempercepat langkahku.
Tak terasa, langit sudah gelap. Lampu-lampu perumahan warga sudah mulai nampak. Aku menoleh untuk mengucapkan terimakasih pada wanita misterius tadi, namun dia sudah menghilang. Sontak aku berlari secepat kilat.
Semalaman aku memikirkan wanita misterius itu, bayang-bayang wajahnya menghantui. Esok pagi aku memberanikan diri untuk menemuinya, aku telusuri jalan setapak seperti sore itu. Sesampainya, ternyata terdapat goa yang cukup besar, kembali bulu kudukku merinding. Perasaan dingin ditengkuk menghembus, batinku memaksa untuk melihat ke dalam goa. Dengan langkah berat, aku memaksakan diri untuk masuk. Aroma melati menyengat menusuk tajam ke lubang hidung. Sontak mataku tertuju pada siluet tak jelas di dalam goa.
“Ternyata kau merindukanku”, ujarnya lembut.
Perlahan aku mendekatinya, mengambil tangannya dan kemudian tertawa bersamanya.
Waktu berlalu, goa seakan menjadi rumah kedua bagiku. Wanita misterius itu selalu mengajakku menikmati senja, merasakan desir angin laut yang bau amis. Hampir tiap hari aku menemuinya. Sehingga emak mulai curiga melihat gelagatku. Emak mulai menginterogasi dengan tajam.
“Aku cuma ke goa panyeppen mak”, santai.
Sontak Emak terkejut, dan menamparku.
“Ali, disana itu tempat angker. Jangan bilang kamu sudah menemui nya”.
Lantas Emak bercerita, dahulu ada seorang gadis muda yang sering menampakkan diri saat matahari terbenam. Ia keluar dari rimbunan hutan cemara yang lebat, dipinggiran hutan bakau yang rimbun. Ia akan bernyanyi menarik hati para pemuda kampung untuk menemuinya. Konon, para nelayan, para pencari perceng, selalu menutupi telinganya dengan kapas agar tidak mendengar suara merdunya. Jika seorang pemuda sekali mendengar suaranya, maka ia akan terjalin erat dengan wanita misterius itu.
Mendengar cerita karangan Emak (aku menganggapnya karangan). Aku tetap bergeming, aku tidak percaya dengan cerita itu. Bahkan Emak bilang bahwa perempuan itu makhluk halus. Aku semakin marah dan menyangkal ucapan Emak.
Aku berlari dengan kaki telanjang, hamparan pasir putih yang halus membuat lambat laju lariku, telapak kakiku tenggelam ringan. Sore hari kembali aku menemuinya, wanita misterius itu tersenyum manis kepadaku. Aku memeluknya erat hingga aku bisa merasakan aroma tubuh dan sentuhan payudaranya. Perlahan aku melihat ke arah wajahnya.
“Astaga”. Wajahku pucat pasi.
Wajahnya datar seperti papan kayu yang baru diampelas. Mata indah, hidung bangir, dan bibir ranumnya lenyap entah kemana. Aku berusaha keras untuk melepaskan dekapannya, namun apalah daya, ia terlalu kuat.
Bersamaan dengan matahari yang mulai terbenam, pasir-pasir putih tak lagi cerah, tiupan angin berhembus kencang hingga menggoyangkan pohon cemara yang rimbun. Perlahan, suaraku hilang di dekapan wanita misterius tanpa wajah.
Esoknya para warga mulai memukul kentongan dan barang apa saja yang dapat berbunyi,
“Ali dimana kamu?”.
“Pulang Li, Emakmu menunggu dirumah”.
Suara kentongan dan teriakan sayup-sayup tenggelam dibalik rimbunnya pohon cemara.
Sumenep, 06 Mei 2025
M. Mufidi